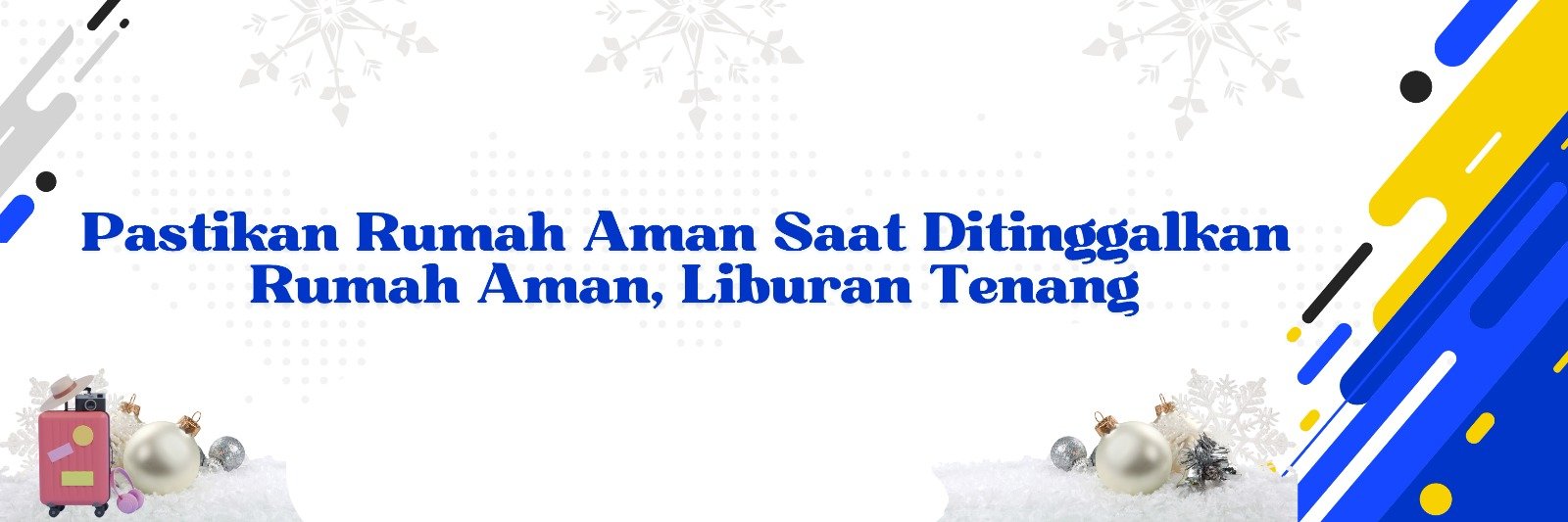Oleh: Via Ratna Handayani
Mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang
Pamulang, – Perkembangan teknologi digital berlangsung semakin cepat dan agresif. Kecerdasan buatan, sistem otomatis, dan berbagai platform digital hadir sebagai simbol kemajuan yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi. Teknologi seolah dirancang untuk memangkas beban manusia dan membuat hidup terasa lebih ringan.
Namun, realitas yang dirasakan banyak orang justru berbeda. Di tengah teknologi yang semakin pintar, manusia malah semakin sering merasa lelah. Lelah secara fisik, mental, bahkan emosional.
Ironisnya, kelelahan ini muncul justru di era yang katanya serba dimudahkan.
Kelelahan tersebut tidak selalu terlihat. Ia hadir dalam bentuk tekanan untuk selalu responsif, tuntutan produktivitas tanpa jeda, serta ekspektasi untuk terus mengikuti ritme digital yang tidak pernah berhenti. Notifikasi datang silih berganti, pekerjaan bisa diakses kapan saja, dan batas antara waktu kerja serta waktu pribadi semakin kabur. Teknologi yang awalnya membantu justru menghapus ruang untuk benar-benar berhenti.
Di dunia kerja, teknologi sering dijadikan pembenaran untuk menaikkan target dan beban kerja. Proses yang lebih cepat dianggap sebagai alasan untuk menuntut hasil yang lebih banyak. Manusia diperlakukan seolah memiliki kapasitas yang sama dengan mesin selalu siap, selalu tersedia, dan jarang diberi ruang untuk gagal atau lelah. Padahal, teknologi boleh berkembang, tetapi tubuh dan pikiran manusia tetap memiliki batas.
Selain itu, teknologi juga membentuk budaya serba cepat dan serba instan. Segala sesuatu diukur dari kecepatan: seberapa cepat membalas pesan, menyelesaikan tugas, atau mencapai pencapaian tertentu. Dalam budaya ini, istirahat sering dianggap sebagai kemunduran, bukan kebutuhan. Kelelahan dinormalisasi, bahkan dibanggakan, seolah menjadi bukti bahwa seseorang cukup produktif dan relevan.
Masalahnya, teknologi tidak memiliki empati. Ia tidak mengenal kelelahan mental, kecemasan, atau tekanan emosional. Sistem hanya membaca data, bukan kondisi manusia di baliknya. Ketika teknologi dijadikan tolok ukur utama produktivitas dan keberhasilan, manusia perlahan kehilangan kendali atas ritme hidupnya sendiri.
Di sinilah letak persoalan yang sering luput disadari. Teknologi tidak salah, tetapi cara manusia menggunakannya sering kali tidak berpihak pada manusia itu sendiri. Alih-alih menjadi alat yang membantu, teknologi berubah menjadi standar yang memaksa manusia untuk terus menyesuaikan diri. Mereka yang tidak sanggup mengikuti ritme ini kerap dianggap tidak adaptif, padahal yang terjadi adalah kelelahan yang nyata.
Jika dibiarkan, kondisi ini akan menciptakan generasi yang terus bergerak tanpa sempat memahami ke mana arah langkahnya. Manusia sibuk mengejar efisiensi, tetapi kehilangan keseimbangan. Produktivitas meningkat, tetapi kualitas hidup justru menurun.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi seberapa canggih teknologi yang diciptakan, melainkan untuk siapa teknologi itu bekerja. Jika teknologi terus berkembang tanpa kesadaran dan batas yang manusiawi, maka kelelahan akan menjadi harga yang harus dibayar. Dan dalam perlombaan kemajuan yang tak pernah berhenti ini, manusialah yang paling dulu kehabisan tenaga.(**)